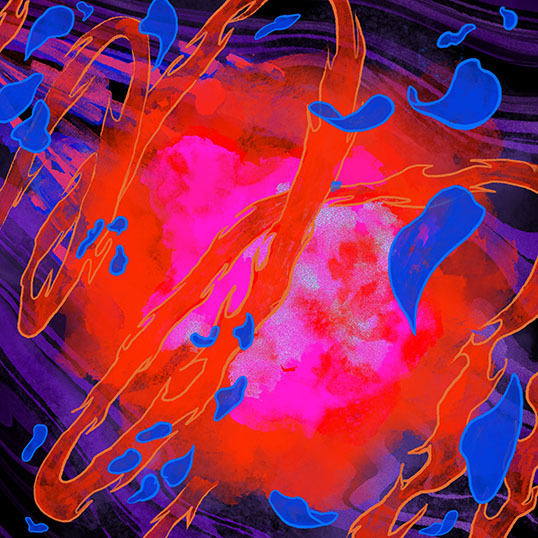Berbaring ia telentang, nungging, telungkup, duduk memegangi pipi serta terus mengeleng-gelengkan kepala menahan sakit yang melandanya tanpa ampun. “Sakittttt... anjiiiiing! Anjiiiiing. Ahhhhh... anjiiiiing,” begitu ia menganjing-anjingkan denyut-denyut di mulutnya. Kadang berteriak, kadang ia redam hingga kedengaran seperti cicit-cicit tikus.
Setelah berhari-hari—hari kelima belas sejak siksaan itu muncul pertama kali cuma sebagai denyut sepele—ia memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Tangannya gemetaran saat memungut palu itu dari ruang belakang. Tapi dengan penuh kelegaan, dia menghembuskan nafas terakhir. Empat hari kemudian, tetangganya, seorang bocah yang suka dengan dongeng-dongeng cabul kemerahan si lelaki tua, menemukannya telentang dengan kening berlumur belatung.
Sekelompok warga melemparkan mayatnya ke jurang di balik bukit. Bisik-bisik terdengar dan ketakutan menyebar. Orang-orang takut ia jadi hantu. Dulu seorang lelaki bunuh diri dan menjelma jadi jembalang curut raksasa. Namun seorang ibu tidak takut masuk ke rumah itu, untuk beres-beres, termasuk membereskan gigi-gigi yang tanggal serta kolam-kolam kecil merah yang mengental. Ia kumpulkan semuanya ke dalam plastik hitam lalu ia masukkan ke dalam bak sampah. Tidak ada yang tahu, kecuali seekor kucing putih borokan dengan titik hitam di dahinya, bahwa tepat tengah malam, gigi-gigi, kranium dan darah yang terkumpul dalam plastik hitam itu berubah menjadi makhluk yang belum pernah ada sebelumnya. Si kucing kelaparan mengais-ngais kantong plastik tersebut sampai robek. Isinya berceceran, menyatu dengan sebuah kondom bekas, akar-akar kangkung, tanah hitam, empat puntung rokok, dan satu batang wortel.
Sebatang wortel berada di situ saat kemarin subuh tercecer dari langit yang retak oleh oranye. Pangkalnya busuk, sehingga tidak jadi dipakai melengkapi semangkok sup ceker bayi yang dimasak para kuntilanak di sebuah loteng yang telantar. Empat puntung rokok berasal dari empat bibir yang berbeda. Seorang pegawai rendahan, seorang wanita pelacur yang tengah hamil, seorang idiot yang dipaksa merokok oleh sekelompok berandalan sebelum disuruh ngocok pakai afitson, dan seorang gadis cantik bergigi hitam. Akar-akar kangkung dibuang oleh seorang wanita tua yang tinggal lima belas blok jauhnya dari sini; wanita pembantu yang disuruh memasak cah kangkung bertabur arsenik secukupnya sebagai makan siang anak tiri seorang nyonya muda. Dan terakhir, kondom kekuningan berisi cairan kental yang teronggok di sudut bak sampah itu setengah jam yang lalu dibuang oleh seorang tukang ojek sehabis memuaskan denyut kelaminnya di dalam pantat seorang waria pada keremangan gang yang sempit dan becek.
*
Bulan bulat melirik jorok pada kota yang lembab dan amis ketika malam mendesah-desah diam. Cahayanya bias mati pada taman genteng bebercak daki hitam. Irama teror angin menggesek-gesek dinding dan daun pintu. Tiap orang terbolak-balik dalam tidur gelisah. Tak ada mimpi indah, tak ada mimpi basah. Yang ada ialah mimpi tentang makhluk buruk yang merayap dalam gelap. Langkahnya terombang-ambing selagi ia menaiki anak-anak tangga dalam sebuah rumah yang gulita. Suaranya gugu, tangis bisu yang timbul tenggelam dalam tenggorokan; sayup, tetapi cukup untuk membangunkan seorang nenek buta dari tidurnya yang terang, hingga ia terduduk di ranjangnya yang dingin dan berkeriut.
“Siapa itu?” tanya si wanita tua buta bernama Osirrah. Ia merasa seseorang tengah berada di kerkah pintunya, namun jawaban yang diterimanya cuma sedu yang mengambang di kegelapan. Makhluk itu ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tidak memiliki mulut untuk berbicara andai pun ia mampu berbahasa, meski ia punya mata di ujung dua puntung rokok yang menjadi tangannya. Ia maju dan kedua puntung rokok yang menjadi kakinya terantuk sesuatu; sakit, menurut pikirannya yang sederhana.
“Awas, ada paku di situ,” kata nenek.
Ah, makhluk itu pun mendapatkan ide—yang sederhana, tentunya. Ia menghunjamkan bagian teratas tubuh wortelnya hingga menancap ke kepala paku yang sedikit mencuat dari permukaan lantai kayu. Ia angkat badannya, lalu dari bolongan yang terbentuk di situ, keluarlah deras tangisnya memekik membahana. Si wanita tua buru-buru—meski pelan, mengingat usianya—turun dari tempat tidurnya mendekati sumber teriakan. Matanya yang tak memandang telah menjadikan telinganya sedemikian peka, sehingga ia tahu tepat di mana makhluk tersebut berada. Mula-mula ia mengira siapapun itu yang sedang menangis pastilah tengah duduk atau jongkok atau telungkup atau telentang. Sebab tubuh makhluk ini pendek, sependek wortel rata-rata. Setelah ia memegang rambut akar kangkung, punggung bergerigi gigi-gigi serta baju kondomnya yang berlendir, si wanita tua pun sadar bahwa ia tengah berhadapan dengan sesuatu yang berasal dari mimpinya baru saja.
Ya, dia bisa bermimpi, karena ia tidak buta sejak lahir. Ia masih menyimpan-ingat citra-citra dari benda-benda yang sempat ia lihat sebelum ia berumur lima belas tahun, ketika kakinya terpeleset di atas lantai licin dan sepasang matanya tersayat tepian kaca. Citra-citra purba saling berbaur dalam khayal atau bunga tidurnya, mempertontonkan cerita-cerita yang biasanya dimulai dengan dinding-dinding yang meleleh dan diakhiri dengan leleran busa putih. Kini salah satu makhluk dari mimpinya telah mewujud ke dunia-raba. Ia angkat makhluk itu dalam tangkupan kedua tangannya, menggoyang-goyangkannya, lalu ia berkata, ”Ssh, ssh, jangan menangis, sayang. Aku di sini; ibumu ada dekat di sini. Tidak pernah aku sangka mimpiku akan jadi nyata untukku. Kau anak yang lahir dari dunia-sepi, maka kuberi kau nama Floccinaucinihilipilificatius, dan akan aku panggil kau Flocci.”
*
Nenek buta Osirrah mempunyai seorang anak gadis berusia tiga puluh tahun bernama September. Orang-orang yakin September terserang penyakit mental karena ia selalu tertawa-tawa; bahkan ketika tidur ia masih akan mengekek-ngekek riuh rendah. Baginya, dunia adalah tempat yang lucu dan membahagiakan sehingga ia tidak hendak menunjukkan ekspresi apa pun dari mulut, mata dan gerak-geriknya selain senyum, kikik dan gelak. Meskipun semestinya ia tidak menyukai anak-anak yang senantiasa menyoraki serta melemparinya ketika ia berada di jalanan atau berada di warung berbelanja, ia gembira saja ketika satu kerikil tajam merobek pipinya, sementara anak-anak itu bersorak-sorai, “Ember gila, Ember gila!”
September tertawa terbahak-bahak sampai air matanya mengalir ketika ia pertama kali melihat Flocci. Osirrah dan Flocci akhirnya turut pula tertawa-tawa. Osirrah lalu berkata, “Ini Flocci, September. Ia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Aku akan mendidiknya, sedangkan kau harus memperlakukannya dengan lembut sebagaimana aku tak pernah membentakmu, memarahi ataupun menyakitimu secuil kulit pun. Selama ini kau teramat kesepian tanpa saudara dan teman, maka anggap dia sebagai adik kandungmu sendiri. Rukun-rukunlah kalian, bahkan setelah aku tiada.”
Mata September berbinar-binar. Diambilnya Flocci dari samping ibunya dan dibawanya ke basin tempat mencuci piring. Keran ia putar, dan penuh dengan keceriaan September memandikan Flocci yang menjerit-jerit manja dan ikut tertawa-tawa dengannya. Rambut akar kangkung dicukur rapi dan gigi-gigi di punggungnya dibersihkan dengan odol dan sikat. Hari itu serta hari-hari berikutnya berlalu begitu tentram dan nyaman bagi Flocci di bawah lindungan dan kasih sayang kedua perempuan anak-berbunda itu. Sampai suatu hari, sakit yang sangat hebat melanda punggung Osirrah.
Nyeri di bagian belakang tubuh Osirrah membuncah sebagai sepasang tulang sebesar ibu jari yang mencuat dari bawah pundaknya. Jeritannya melengking-lengking siang-malam dan pagi. Ia tak dapat tidur. September dan Flocci menunggui di kanan-kiri ranjangnya tanpa tahu harus berbuat apa. September tertawa-tawa sepanjang waktu selagi Flocci meraung-raung mencucurkan air mata darah. Jerit, tawa dan tangis menggaung di dalam rumah besar mirip puri itu, di pinggir kota yang langu oleh ramai. Di kota ini, suara macam apa pun tidaklah perlu dipertanyakan atau dibesar-besarkan. Sehingga tak ada yang memerhatikan selain kedua anaknya, bahwa Osirrah berangsur-angsur kehilangan suara untuk berteriak. Tetapi kedua tulang di punggungnya terus mencuat; mencuat sepanjang jengkal, lalu sepanjang lengan, dan bulu-bulu putih tumbuh di sana. Flocci dan September sadar, tak lama lagi ibu mereka akan pergi.
Karena Osirrah pernah bercerita:
Aku bukan manusia; aku adalah malaikat yang menjalani ujian di dunia-bawah sebagai anak Ilya, pelacur dari Athena. Aku adalah ruh suci yang ditiupkan ke dalam rahim cadas yang telah dibuahi satu sperma hina. Ketika aku lahir, orang-orang takjub melihat tubuhku yang bersinar. Mereka bilang, anak ini pasti titisan dewa matahari, dan ketika aku berumur lima tahun, sebuah suara bernyanyi bergemerincing di kepalaku: Putih dan hitam tak patut berpadu, jangan kau tanya kebenarannya pada lembar-lembar yang palsu. Sudah waktunya mentari dan bulan mengalahkan awan, fajar mengalahkan kelam dan kolam cahaya membasuh segala najis kotoran. Panggillah mereka ke jalan terangmu, perempuan pilihan.
Aku terpilih sebagai seorang pembaharu, anak-anakku, dan nyanyian itu terus-menerus mendatangiku. Akan tetapi, begitu umurku membilang belasan dan darah kecoklatan untuk pertama kalinya mengalir deras dari liang selangkang, sinarku meredup cepat dalam hitungan hari. Aku pun menyadari bahwa mulai saat itu, hatiku akan dicoreng hitam tiap kali aku menyaksikan pemandangan-pemandangan laknat di kawasan perlontean itu. Ibuku dan teman-temannya mulai mengajariku merias diri dan menggoyangkan pinggul menggoda lelaki. Ketika kutolak dan kuberitahu tentang jalan cahaya, mereka tertawa terpingkal-pingkal dan mencemoohku. Kulitku menggelap, sang nyanyian berhenti berfirman. Dalam ketakutanku aku pergi, melarikan diri, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, lintasi daratan dan laut, berlari mengejar garis batas antara malam dan pagi, hingga akhirnya aku kelelahan dan tertidur di depan pintu rumah kita sekarang ini.
Betul, rumah ini. Seorang lelaki tampan membukakan pintu untukku. Jelas ia terpikat oleh kecantikanku, oleh sebab itu ia mengajakku masuk. Dan ketika aku berumur lima belas tahun, aku menikah dengannya. Hanya saja pada malam pengantinku, saat mengalir darah perawanku, aku pingsan, dan satu sayup-sayup bisikan terdengar di kuping: Sekuncup kandil tak semestinya melesat tinggalkan sumbunya, tapi bila terjadi, terjadilah. Sebagai gantinya, biarkan penglihatanmu tinggalkan sarangnya, dan relakan kepompong sayapmu tinggalkan dahannya; boleh kau dapatkan kembali ketika jasadmu dekati mati.
*
“Flocci,” panggil Osirrah parau, matanya mengerjap-ngerjap. “September,” katanya lagi. Perih mengiris bola matanya saat nampak olehnya kedua anaknya tersedu dan tertawa-tawa. Sayapnya telah terentang tinggi-tinggi menyentuh langit-langit. Dan seperti digerakkan oleh satu kekuatan dahsyat, sepasang sayap itu lalu mengibas. Semua yang ada di dalam kamar terhempas oleh angin yang tercipta, termasuk Flocci dan September yang kini duduk melongo di lantai bersandar pada dinding. Tubuh Osirrah menyala, terbakar seperti ranting tersulut api. Segenggam cahaya mengambang di udara ketika api tadi menguap habis. Atap rumah mendadak meledak, menyerpih, sebab dengan kecepatan yang tak terhingga, cahaya itu terbang ke langit yang hitam oleh awan musim hujan. Flocci berteriak memanggil ibunya, ditingkahi lengking suara September yang berniat menyusul cahaya itu dengan berlari menghantam kaca jendela. Tubuhnya terlempar menghempas tanah dan lebur seperti agar-agar. Seketika itu juga tumbuh tunas-tunas hijau di tempat September terjatuh.
Kelak di tiap bulan September, suatu jenis tumbuhan akan berbunga berwarna merah. Kembangnya seperti sepasang bibir yang menganga, mengingatkan siapapun yang melihatnya akan mulut yang lebar tertawa. Flocci tidak sempat melihat tunas itu berbunga. Ia keluar rumah menuju kota. Ujung tangannya terus memandang ke atas, mencari-cari Osirrah, namun jarum-jarum gerimis membuat sepasang mata itu mendesis. Ia melalui gang-gang dan bertemu dengan manusia-manusia yang menjerit melihatnya. “Ibu?” ratapnya saat menemukan seorang wanita tua. “Apa itu?” balas wanita itu, memanggil orang-orang di dekatnya.
“Makhluk apa itu? Dia bisa bicara.”
“Tangkap, tangkap!”
“Injak, injak!”
“Bunuh, bunuh!”
Beramai-ramai orang menangkapnya.
“Apa yang mesti kita lakukan dengan wortel aneh ini?”
“Potong-potong saja. Itu pasti makhluk terkutuk.”
“Siram dengan air keras, lalu kita taruh di museum.”
“Jangan ngaco, kita tidak punya museum.”
“Kita buat nanti.”
Mereka setuju untuk menaruh Flocci di suatu museum. Selama sebulan penuh mereka bekerja keras membangun sebuah museum kecil di tengah tanah lapang tempat tubuh mati Flocci bakal dipajang. Tapi, selama sebulan itu para warga ternyata bisa mengembangkan pikiran untuk berbisnis. Bukankah lebih menarik kalau makhluk ini tidak dibunuh, melainkan ditaruh saja di dalam suatu kotak kaca? Beri bolongan kecil di atasnya, siapa tahu dia perlu bernafas. Yang ingin melihat harus membayar. Mungkin makhluk ini bisa diajari menari atau menyanyi, supaya yang datang lebih senang. Buat pemberitahuan ke kota sebelah, ke pulau seberang, ke negeri tetangga, ke benua terjauh sekalian. Uang akan mengalir masuk dan warga kota dapat mengelolanya demi kemakmuran bersama, dengan para petinggi mendapatkan bagian yang lebih besar tentunya.
Maka begitulah Flocci dikurung dalam kungkungan kotak kaca segi empat. Mereka memberinya air buat diminum dan sup kacang untuk dimakan. Di tahun berikutnya pengelola museum membuatkan kotak kaca yang lebih besar, sebesar lemari, sudut-sudutnya disepuh emas. Kini mereka menyediakan untuknya susu dan daging uap. Tiap tahun sangkarnya diperluas, dan makin enak pula makan dan minum yang diberikan kepadanya. Seluruh dunia tampaknya ingin melihat si jenglot wortel yang bisa bicara, meskipun ia sendiri ingin lepas untuk naik ke langit. Ia sudah mengutarakan hal ini berkali-kali, lewat suaranya yang kecil dan kata-katanya yang terbatas. Namun siapa kiranya yang sudi untuk mengabulkan?
“Sudah kamu diam saja,” kata Walikota. “Kamu seharusnya bersyukur bisa hidup enak macam ini. Apa belum cukup kami memeliharamu dengan perlakuan yang mewah sebagai tanda terima kasih karena sudah membuat kami semua kaya raya?”
“Pertemukan aku dengan ibuku,” pinta Flocci, untuk kesekian kali.
“Ibu macam apa yang dapat melahirkan keganjilan seperti kamu?”
Mau bagaimana lagi? Flocci mesti pasrah menerima nasibnya sebagai bahan tontonan. Akan tetapi, di penghujung tahun kelima terkurungnya ia di dalam kaca, suatu kehebohan terjadi. Selembar hantu melayang-layang rendah menuju museum. Orang-orang menyingkir ketakutan, terlebih-lebih karena hantu itu memegang sebilah martil di tangan kanannya. Hantu itu terus terbang mendekati tempat Flocci berada. Sesampainya di sana, ia angkat martil itu tinggi-tinggi dan ia pecahkan kotak kaca besar di hadapannya hingga berkeping-keping. Kemudian ia tarik tangan Flocci, membawanya menuju puncak bukit di utara.
“Hanya setinggi ini aku bisa membawamu,” tutur hantu itu selagi mendarat.
“Harus lebih tinggi lagi,” pinta Flocci. “Ibuku ada di atas sana.”
“Jangan khawatir, Nak, udara akan membantumu,” dan puf, ia lenyap.
Flocci merasakan hembusan angin berputar-putar di atas kepalanya. Ia lihat, debu-debu yang diterbangkan ringan oleh udara menyatu membentuk tali yang menjulur ke langit. Flocci melompat kecil menangkap tali itu, memanjat dan merambat, hari demi hari. Begitu ia mengira sudah amat dekat dengan ujung teratas, bersusunan pulalah lagi debu-debu itu memperpanjang perjalanannya. Bersama kenangan akan ibunya, Flocci gigih membolongi perisai atmosfer. Ia tidak lagi menghitung berapa kali sudah sinar matahari mendatangi dan meninggalkannya, karena toh ia sudah teramat jauh dari bumi. Ia lewati bulan, ia songsong planet-planet, bertamasya ke negeri tak bertuan dan tanpa suara.
Pun demikian, di antara dua degup yang serasa abadi, Flocci macam disadarkan bahwa ia tak paham siapa dirinya, apa yang sedang ia lakukan, atau mengapa ia merasa panas sekaligus membeku. Darah dalam tubuhnya susut dan ia lemas. Panjatannya melambat, terus makin perlahan, hingga akhirnya ia berhenti. Pegangannya mengendur, lepas, dan jalinan debu-debu memencar-pecah meninggalkannya. Lengang tak bertepi. Flocci melayang-layang dalam vakum angkasa untuk waktu yang tak bertara. Nirkala. Nyaris selamanya.
*
Floccinaucinihilipilificatius menghidupkan bara terakhir yang masih bertahan di matanya. Ia mendengar sesuatu. Ia tangkap sebuah dengung seolah air bah yang mendesau menggulung menuju dirinya yang telah kering. Oh, ia melihat cahaya terang. Bukan, tak hanya terang; menyilaukan. Sebuah bola pijar menderu ke arahnya. Membesar dan makin membesar sampai dia paham bahwa bulatan raksasa yang menyilaukan itu adalah sebuah bintang berekor. Seketika pandangannya buta sewaktu cahaya itu merengkuhnya ke dalam panas yang lembut. Ia mengenalinya sebagai cita bernama kasih. Ia berujar pada dirinya sendiri, ia tidak tengah bermimpi, ini adalah pertemuan yang sudah ia nanti-nantikan begitu lama; ia berada dalam pelukan ibunya, segenggam cahaya yang telah malih menjadi komet Osirrah dengan ekor berjarak ratusan tahun cahaya. Leburlah, leburlah, anakku, ke dalam kasih ibumu yang melesat tiada henti dalam pencarian.
Ia membiarkan dirinya terbakar, menyisakan setitik cahaya yang tak perlu lagi mencari. Ia melesak menjadi inti bagi ibunya, bersama-sama melintasi surga tujuh puluh lapis. Para bidadari melemparkan bunga-bunga merah delima ke arah mereka, merestui pertemuan yang begitu mengharukan bagi langit dan bumi, hingga selama beberapa saat dunia-atas membentangkan jalan bagi dunia-bawah dan sekelompok malaikat mengizinkan semua yang bercahaya membakar dirinya untuk dapat terbang membuntuti komet terbesar di semesta raya.
Sejak saat itu, Flocci dan Osirrah bersama-sama bercahaya bahagia untuk selama-lamanya.